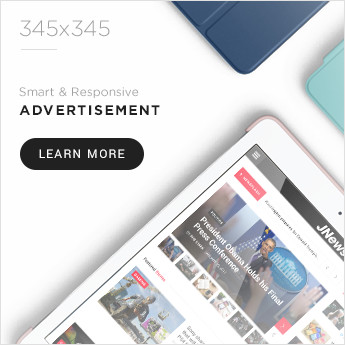Jakarta, newtechclub.com – Dosen Ketahuan Pakai ChatGPT. Seorang mahasiswi Northeastern University di Massachusetts, Amerika Serikat, geram setelah mengetahui dosennya memakai ChatGPT untuk menyusun materi perkuliahan. Tak terima, Ella Stapleton—nama mahasiswi itu—langsung menuntut kampusnya mengembalikan uang kuliah sebesar $8.000. Pasalnya, sang dosen kerap melarang mahasiswa memakai AI, tapi ternyata sendiri mengandalkan chatbot untuk pekerjaannya.
Baca Juga: China Bangun Jaringan Komputer Super di Antariksa, Buat Apa?
Stapleton awalnya tidak curiga sampai suatu hari ia melihat prompt ChatGPT masih tertinggal di materi kuliah. Tertulis jelas perintah seperti “expand on all areas. Be more detailed and specific.” Spontan, ia memeriksa ulang slide presentasi dosen dan menemukan banyak kejanggalan. Mulai dari typo kasar, teks berantakan, hingga gambar tidak relevan—kesalahan khas AI yang kurang akurat.

Stapleton memang gagal memperoleh pengembalian uang kuliah, namun laporannya berhasil mendorong sang dosen untuk merevisi materi perkuliahan. Dosen tersebut akhirnya mengaku, “Saya harusnya mengecek ulang output ChatGPT lebih cermat.” Sementara itu, Northeastern University tetap membuka pintu bagi pemanfaatan AI dalam perkuliahan, dengan syarat wajib mencantumkan label penggunaan AI dan melakukan verifikasi manual guna mencegah hallucination atau informasi menyesatkan dari sistem AI.
Tak hanya di Northeastern, seorang mahasiswa Southern New Hampshire University juga mengeluhkan dua dosennya yang lupa menghapus prompt ChatGPT di esai feedback. Mahasiswa itu kesal karena merasa tugasnya tidak dibaca sungguh-sungguh. Salah satu dosen membantah, tapi fakta bahwa prompt AI masih terbaca jelas memperkuat tudingan mahasiswa.
Sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT di tahun 2022, para pendidik mulai merasakan dampak frustasinya. Seorang guru kelas 10 mengeluh, “Siswa-siswa saya sekarang malas membaca karena terlalu bergantung pada AI yang membacakan teks untuk mereka.” Lebih parah lagi, banyak siswa yang terbiasa mengandalkan ChatGPT untuk mengerjakan soal-soal dasar, lalu langsung ngamuk saat diminta menulis tangan di kertas.
Para pengajar sebenarnya sudah piawai membedakan karya mahasiswa asli dan buatan AI. Dosen atau guru yang malas mengecek hasil AI justru memperparah keadaan. Seperti kasus Stapleton, alih-alih memudahkan, ketergantungan pada ChatGPT malah merusak kredibilitas pengajar.
Northeastern University berusaha menengahi dengan mewajibkan watermark pada konten AI. Sayang, banyak dosen terburu-buru dan lupa memastikan keakuratan output-nya.
Stapleton dan mahasiswa lain menuntut keadilan. Bagi mereka, aturan harus berlaku dua arah. Jika kampus melarang mahasiswa mengandalkan AI, maka dosen juga wajib memberi contoh baik. “Ini standar ganda yang merugikan kami,” protes Stapleton.
Kasus-kasus ini memicu debat: haruskah kampus melarang total penggunaan AI, atau justru mengintegrasikannya dengan pengawasan ketat? Sementara sebagian guru khawatir dengan penurunan kemampuan analisis murid, lainnya berargumen bahwa AI adalah tools masa depan yang tidak bisa dihindari.
Masalahnya bukan pada ChatGPT, melainkan cara penggunaannya. Dosen yang malas mengecek materi AI telah mengecewakan mahasiswanya. Di sisi lain, mahasiswa juga harus paham bahwa AI bukan pengganti kerja keras. Jika kedua belah pihak bisa kolaborasi dengan bijak, pendidikan di era digital justru bisa lebih maju.